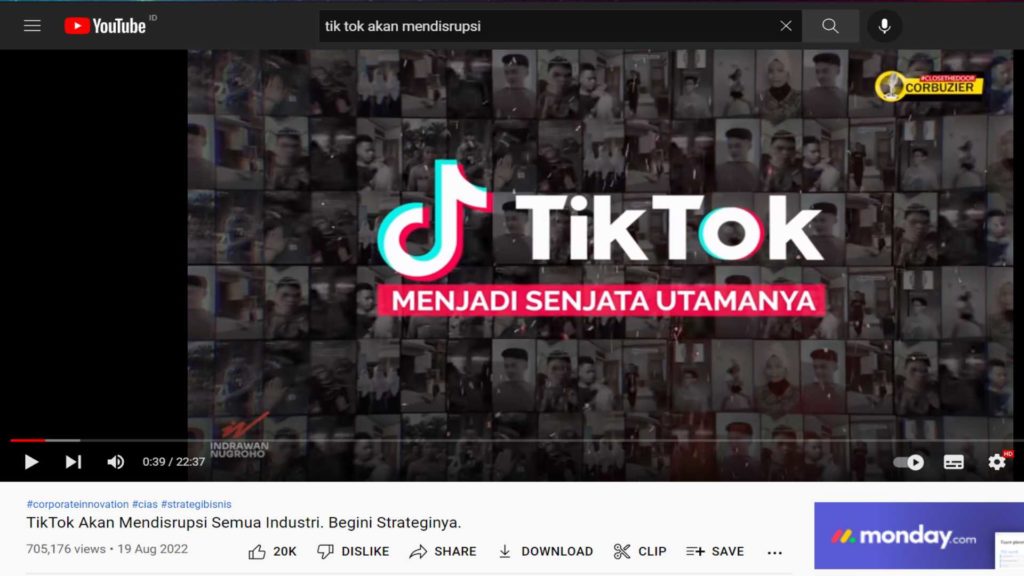Pada 22 Agustus yang lalu, pas sedang mengikuti PAWR (baca postingan saya sebelum2nya), saya mendapat kiriman link video dari seorang rekan seangkatan studi di UI, lewat WA (japri).
Berikut link videonya: https://youtu.be/A6ix5OFAvpE dan kenampakan skrinsyut-nya
Video tersebut, yang pertama kali di-posting pada 19 Agustus 2022, telah viral dan menjadi perbincangan di antara emak-emak yang punya anak sedang bersekolah di jenjang SD, SMP dan SMA (per 2022) karena “menakutkan prediksinya dan, jika benar terjadi seperti yang diprediksi, menyeramkan dampaknya buat anak-anak kita.”
Dalam video berdurasi 22 menit 37 detik yang sudah disaksikan lebih dari 700 ribu pemirsa (views), per 9 Oktober 2022, Dr. Indrawan Nugroho mendaku bahwa “TikTok sedang membangun senjata pemusnah massal yang akan meluluhlantakkan para pemain di berbagai industri. TikTok akan merevolusi konstelasi persaingan bisnis di masa depan.” Benarkah klaimnya ini?
Terlepas dari pro kontra truth-value konten yang disampaikan dan kesahihan metodologisnya sehingga pak Indrawan dapat menarik kesimpulan yang bernada seperti memprediksi masa depan (FYI: halo, siapa sih yang hari begini gak tergoda utk memprediksi masa depan?), saya memiliki beberapa catatan kritis maupun afirmatif terhadap video tersebut.
Pertama, saya tidak serta-merta percaya begitu saja apa yang disampaikan pak Indrawan “hanya dengan menonton video tersebut” kemudian menarik kesimpulan serba tergesa yang entah mengiyakan buta maupun menolak mentah-mentah tesisnya. Saya sudah terbiasa dan terlatih untuk melakukan triangulasi pandangan dengan mencari, membaca & meneliti sumber-sumber lain yang membahas topik yang sejenis, khususnya pandangan para pakar [dalam hal ini saya berseberangan dengan tesisnya Tom Nichols dalam bukunya The Death of Expertise: The Campaign against Established Knowledge and Why It Matters (Oxford University Press, 2017)]. Saya membandingkan klaim utama dalam video tersebut dengan pernyataan seorang ahli psikologi bernama Dr. Julie M. Albright, seorang Profesor di Universitas Southern California (USA) dan penulis buku Left to Their Own Devices: How Digital Natives Are Reshaping the American Dream (2019).
Menurutnya, “Dalam istilah psikologi, keberadaan platform media sosial [seperti Tiktok ini] disebut sebagai random reinforcement. Artinya, terkadang kita menang, kadang kalah. Seperti itulah platform2 media sosial ini didesain…mereka persis seperti mesin judi (slot machine). Yang kita tahu dari mesin judi adalah sifat adiktifnya. Kita juga tahu bahwa ada yang namanya kecanduan berjudi, kan? Tapi jarang kita mendiskusikan tentang bagaimana piranti teknologi yang kita genggam dan berbagai platform/apps yang kita install di dalamnya memiliki kualitas adiktif yang sama seperti mesin judi tadi.” [dikutip berdasarkan wawancara yang dilakukan kontributor senior, John Koetsier, dengan Dr. Julie M. Albright yang dimuat di majalah bisnis terkemuka, FORBES, pada 18 Jan. 2020 lalu. Judul artikelnya lumayan provokatif! Digital Crack Cocaine: The Science Behind TikTok’s Success. Link beritanya di sini: https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/01/18/digital-crack-cocaine-the-science-behind-tiktoks-success/?sh=76f4768578be]
Kedua, saya mengobservasi dan kemudian berasumsi bahwa orang-orang muda yang dibesarkan dengan Internet, telepon pintar, dan media sosial dengan cepat mengubah kebiasaan, nilai, perilaku, dan norma lama menjadi kenangan yang jauh—menciptakan kesenjangan generasi terbesar dalam sejarah. Dalam buku Left to Their Own Devices ini, Albright dengan jeli melihat sejumlah cara yang di dalamnya orang-orang muda, yang difasilitasi oleh teknologi, “tidak terikat” dari aspirasi dan cita-cita tradisional, dan lalu bertanya: Apa efek dari terputusnya hubungan dari gugus tradisional yang sifatnya menstabilkan struktur sosial seperti gereja, pernikahan, partai politik, dan pekerjaan jangka panjang? Apa artinya menjadi manusia ketika ikatan seseorang dengan orang, tempat, pekerjaan, dan institusi sosial melemah atau rusak, tergeser oleh hiperkonektivitas digital? Bagaimana seyogianya gagasan tentang menjadi manusia yang terhubung secara digital (lewat media sosial, misalnya) sekaligus terhubung secara tradisional (lewat perjumpaan dan interaksi tatap muka, misalnya)? Apa plus minus-nya?
Ketiga, saya mengapresiasi pandangan yang disampaikan Prof. Albright dan juga video yang di-posting pak Indrawan tadi guna memahami fenomena saturasi media sosial dalam hidup sehari-hari, khususnya betapa media sosial itu begitu besar dampaknya untuk mengubah bukan hanya cara pandang, tapi juga cara mengada Gen. Z (dan generasi berikutnya), seperti yang cukup sering digosipin oleh sebagian besar emak-emak penjemput anak di sekolah dan yang acapkali memunculkan rasa khawatir yang akut dalam diri kaum cerdik-cendekia dan para penjaga moral masyarakat bahwa, jika tidak diintervensi secara tegas dan proper, anak2 kita akan “rusak kepribadiannya” karena bentukan apps seperti TikTok dan cara MENGADA, termasuk di dalamnya cara berbahasa dan berinteraksi dengan orang lain, yang selalu terhubung secara digital (always on).
Cf: Dua buku berikut ini, (1) Always On: Language in an Online and Mobile World (Naomi S. Baron, 2008) dan (2) Always On: Hope and Fear in the Social Smartphone Era (Rory Cellan-Jones, 2021)
to be continued with
The Negative Impact of Social Media on Youth Mental Health: Do we have to really worry about this?
in my next post.