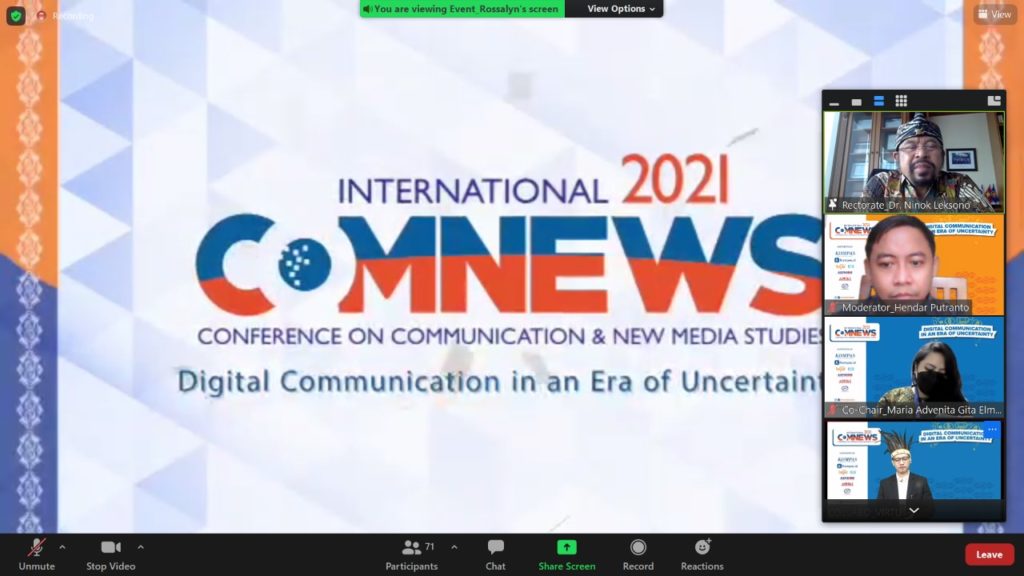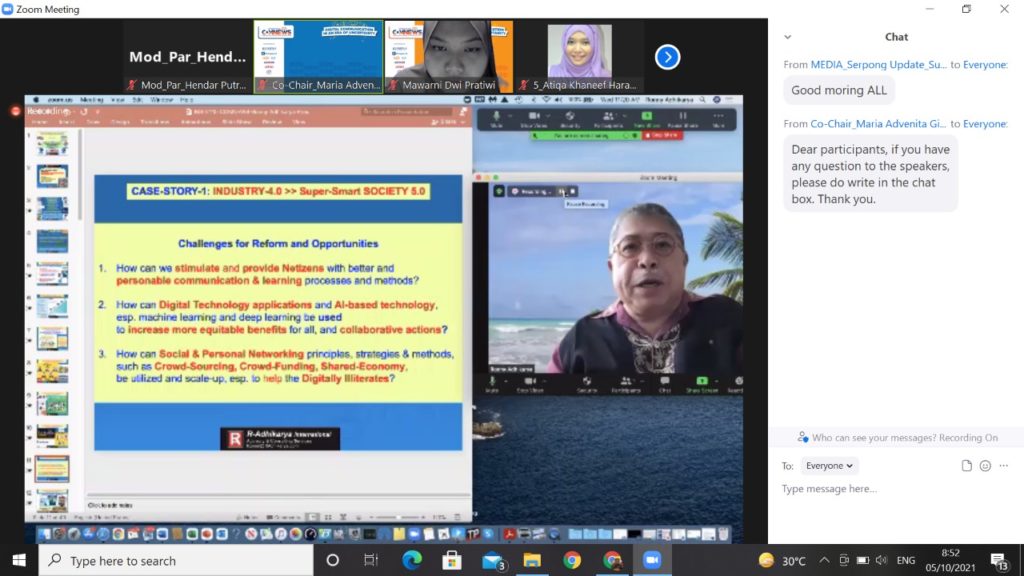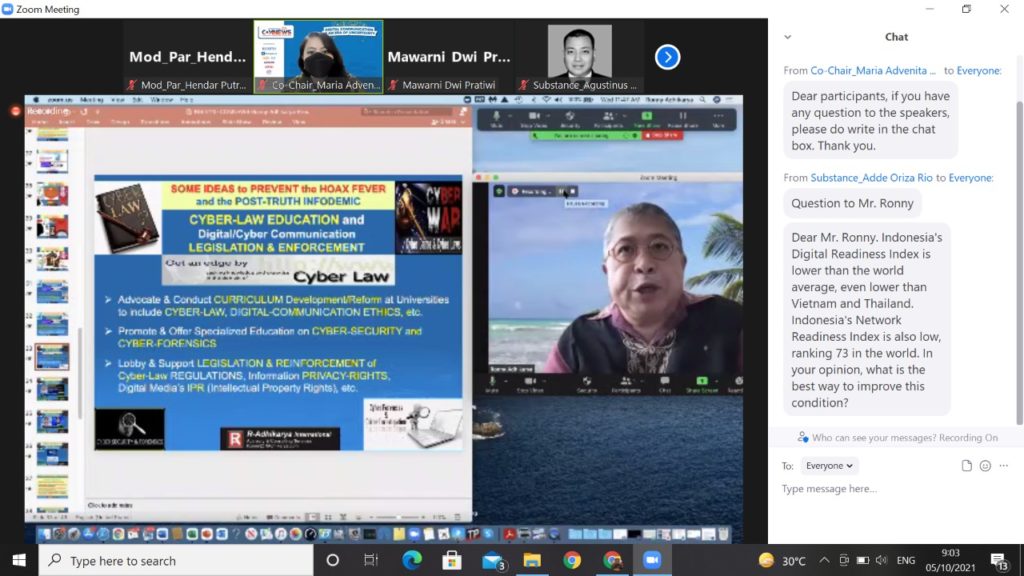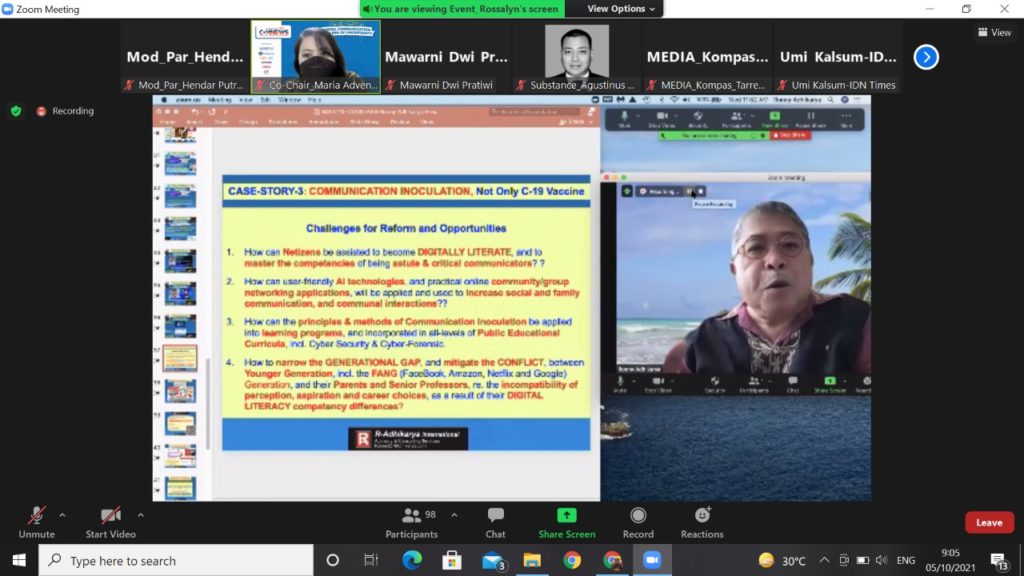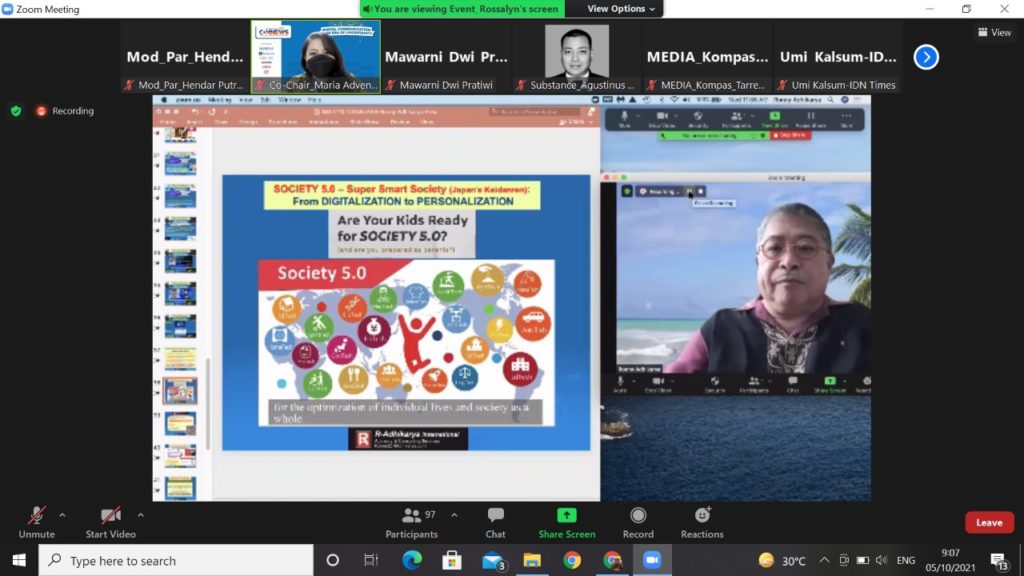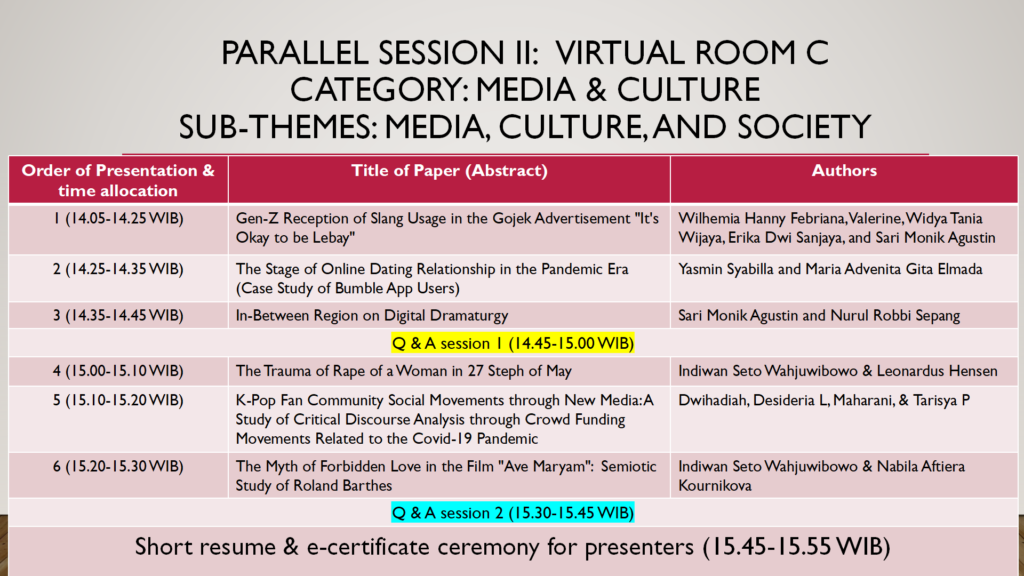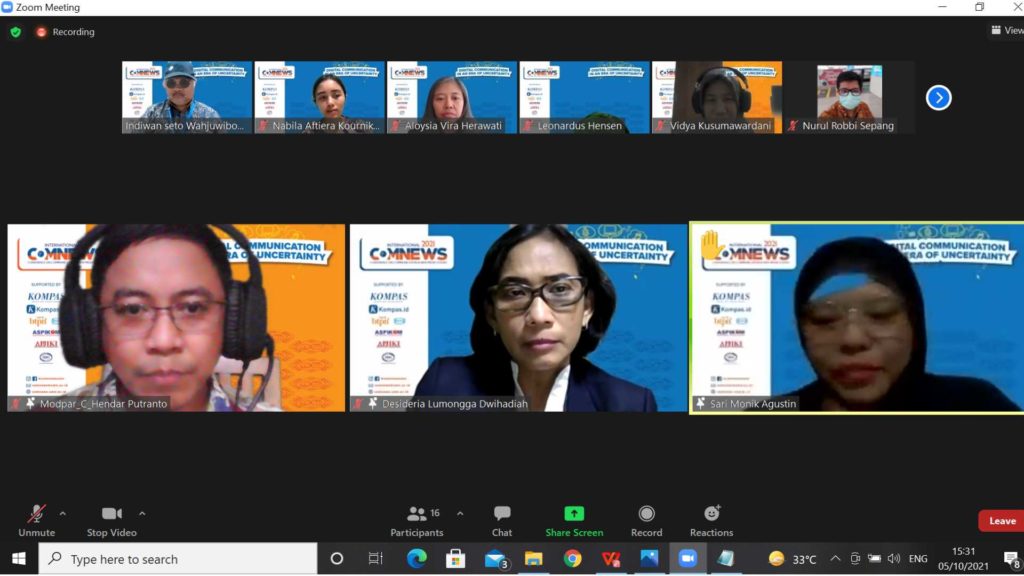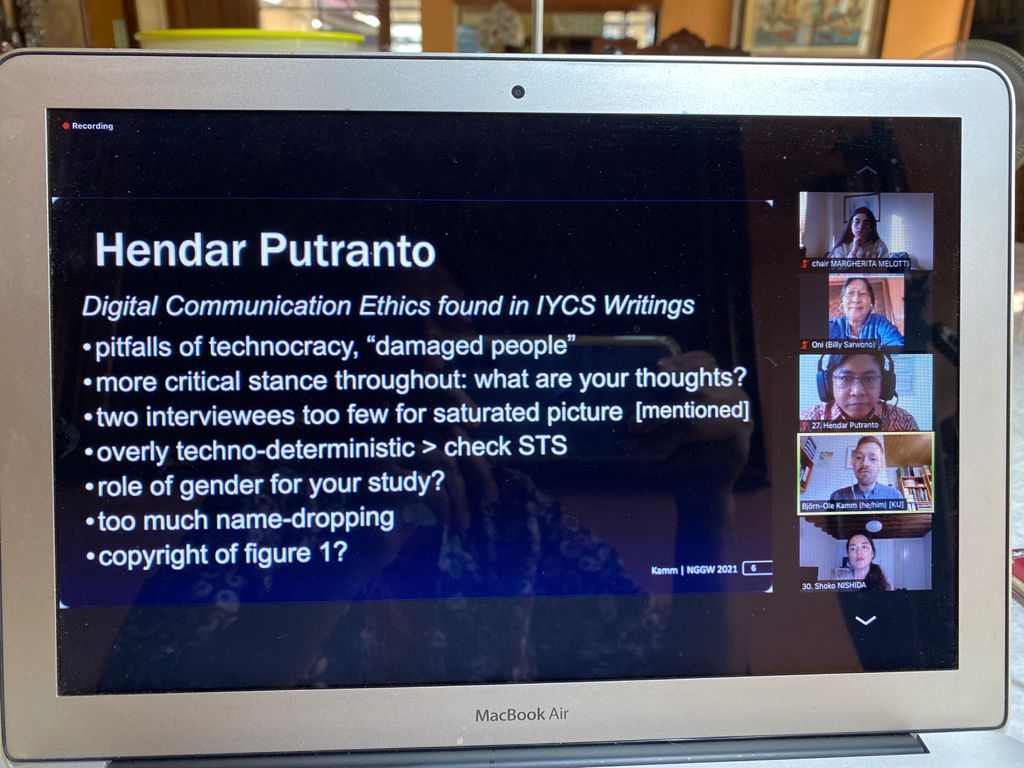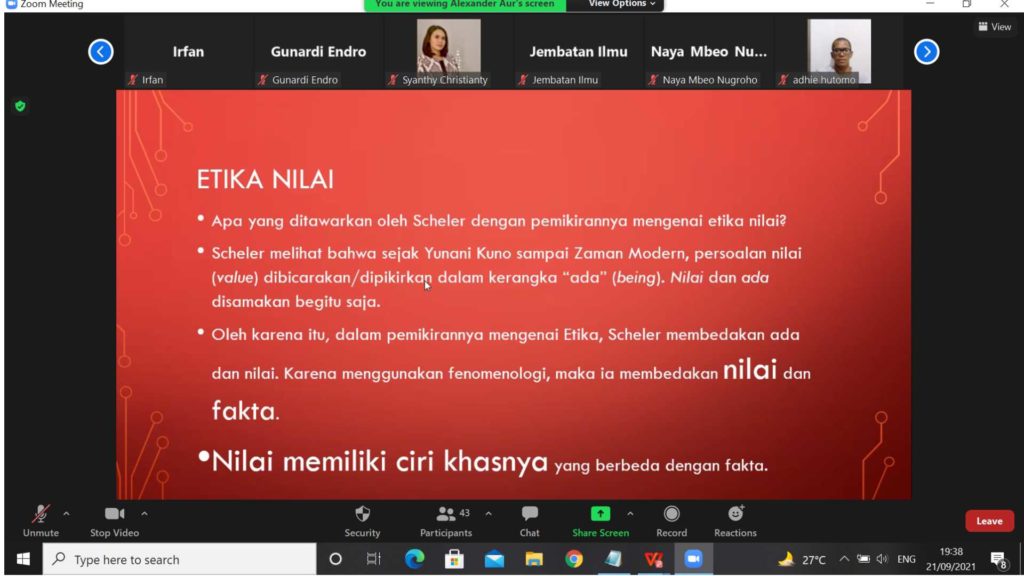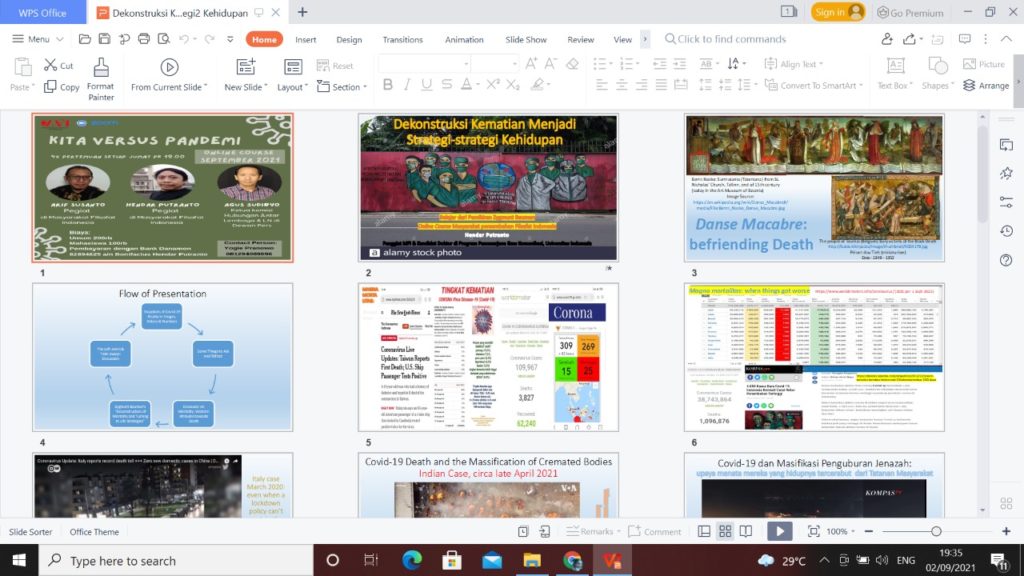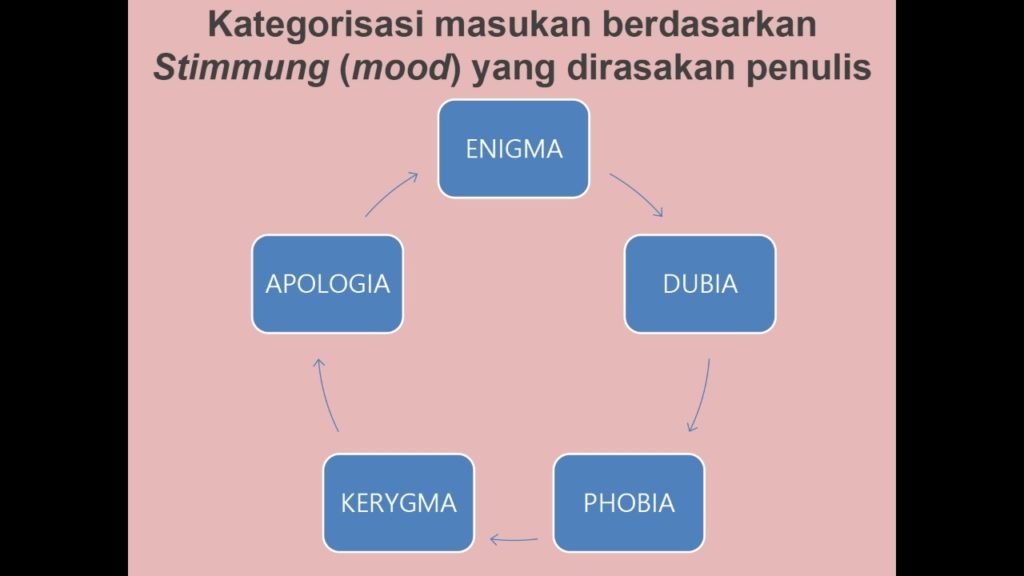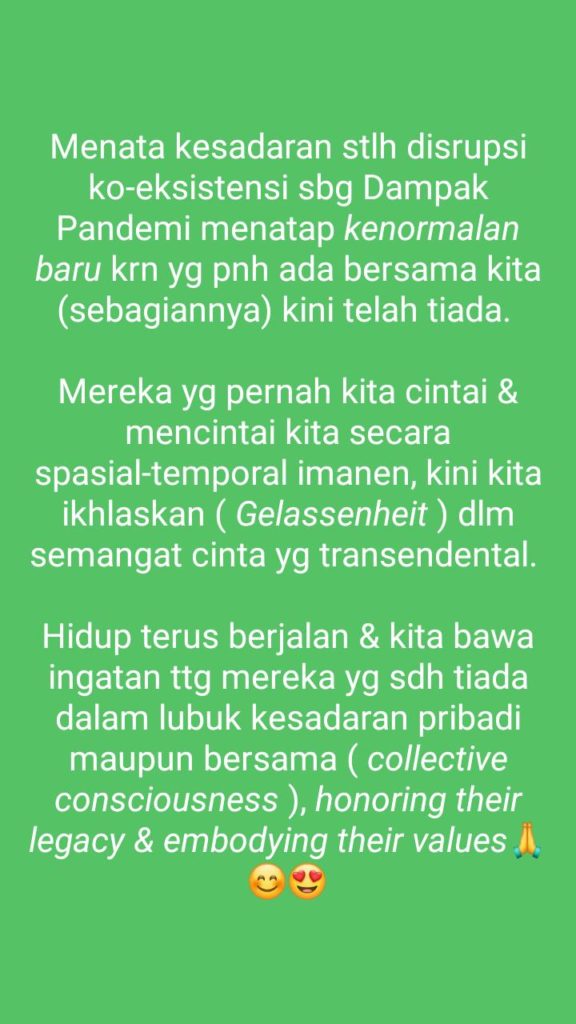[berdasarkan salindia presentasi kelompok 4, nomor 8]
Dari tiga premis yang diajukan Herbert Blumer, murid dari G. Herbert Mead, tentang teori interaksionisme simbolis, yaitu:
1) “Manusia bersikap terhadap orang/benda lain berdasarkan makna yang mereka berikan kepada orang / benda tersebut” (makna)
2) “Makna muncul dari interaksi sosial antara manusia yang satu dengan yang lainnya.” (bahasa) [Meaning is negotiated through the use of language—hence the term symbolic interactionism], dan
3) “Interpretasi simbol dalam diri seseorang dimodifikasi oleh proses di dalam pikirannya.” (pikiran)
Maka, saya memberikan tiga butir tanggapan sebagai berikut:
1. Pada era informasi (ICT, tepatnya) seperti sekarang ini, ketika sikap, makna, dan interpretasi terhadap simbol maupun isi pikiran orang ‘sedikit banyak’ (dan ini lebih dominan terjadi pada generasi yang lahir tahun 2000 ke atas) dipengaruhi oleh media dan informasi dijital, maka sikap, makna, interpretasi dan isi pikiran kita sudah termediatisasi secara dijital, alih-alih interaksi sosial secara langsung face-to-face. Bahasa—yang di antaranya dipahami sebagai konvensi sosial yang terpahami secara kontekstual—yang digunakan oleh generasi sekarang pun relatif berbeda dari bahasa yang digunakan oleh, katakanlah, generasi pada masa hidup dan produksi pengetahuan yang dicetuskan Mead dan Blumer, yaitu rentang tahun 1930-1940-an di Amerika Serikat. Perbedaan bahasa yang menjadi rujukan masyarakat ini pada gilirannya akan membentuk isi kesadaran dan sikap pada serta interaksi yang terjadi antara individu-individu yang menggunakannya, yang juga berbeda.
2. Siapakah ‘aku’ pada saat lahir? Jika merujuk pada pandangan Mead (dalam Griffin, et.al., 2019, h. 59), “there is no ‘me’ at birth. The ‘me’ is formed only through continual symbolic interaction—first with family, next with playmates, then in institutions such as schools,” identitas ‘aku’ adalah konstruksi sosial yang dibatasi oleh konteks sosio-politis-bahasa-dst. Pertanyaan kritisnya, jika memang ‘konstruksi diri aku’ ini terbatasi oleh konteks sosio-politis-bahasa dan lainnya, mengapa tetap ada gagasan serta diskursus universal tentang ‘parenting’ (meskipun isi dan caranya berbeda-beda dari satu budaya ke budaya lainnya)? Bukankah dengan adanya universalitas pemahaman soal parenting ini kita dapat menemukan sejumlah pokok yang sama (sekurang-kurangnya: mirip) tentang parenting lintas budaya? Misalnya, bahwa orang tualah (entah single parent atau sepasang) pihak yang paling bertanggungjawab terhadap pengasuhan anak mereka sampai ia cukup mandiri untuk berdiri di atas kakinya sendiri.
3. Dalam tulisannya, Robinson (2007) menyoroti soal tren kajian pascamodern yang ‘hanya’ memotret persoalan internet self-ing berdasarkan permainan peran dalam Multi-User Domains (MUD) pada masa-masa awal lahir&berkembangnya internet saja (1990-an). Berbagai kajian tersebut ternyata didasarkan pada populasi pengguna internet (saat itu) yang sebagian besar terdiri dari young technically proficient males, yang di dunia luringnya mungkin saja mengalami stigma sosial, sehingga mereka terdorong untuk menciptakan ‘diri mereka yang lain’ di dunia daring. Profil pengguna internet seperti ini sudah tidak lagi menjadi mayoritas dari total populasi pengguna internet sekarang (2007, pada saat tulisan Robinson dipublikasikan). Karenanya, penjelasan pascamodern tentang fenomena cyberself-ing tidak lagi meyakinkan bagi para pengguna internet masa kini dikarenakan perubahan tren populasi pengguna internet dan kegiatan2 yang mereka lakukan selama terhubung (daring). Dari bukti-bukti yang dikumpulkannya, Robinson justru menguatkan kesimpulan soal tesis sebaliknya yaitu ‘socialized’ online selves yang mengambil insight dari perspektif interaksionisme simbolik Mead dan Blumer. Sebagaimana konsep diri luring terbentuk berdasarkan tahapan the ‘I,’ the ‘me’ and the ‘generalized other’ (Mead, 1934), maka diri daring juga ternyata menempuh tahapan yang sama, hanya saja konstruksi jati diri daring tersebut didefinisikan ulang dalam lingkungan daring (in online venues that preserve the dynamics of interactional cuing).
Kesimpulan Robinson, interaksi di ranah siber melanggengkan proses pembentukan jati diri daring yang sudah terlebih dulu ada di dunia luring.
[© Hendar Putranto, 2019]
Rujukan Utama:
Mead, G. H. (1934). Mind, Self & Society. Chicago: University of Chicago.
Rujukan Tambahan:
Robinson, L. (2007). The cyberself: the self-ing project goes online, symbolic interaction in the digital age. New Media & Society, 9(1), 93–110. DOI: 10.1177/1461444807072216